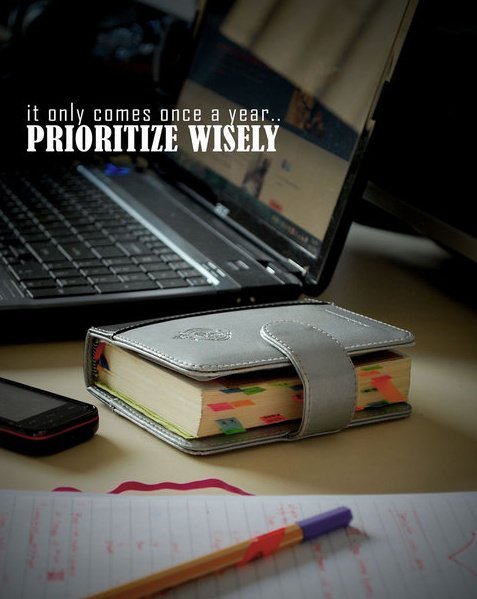“Tak semua orang
bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata”
(Ran dan Tulus –
Kita Bisa)
Hampir setahun belakangan ini saya disibukan dengan pikiran tentang “umum”
dan “tidak umum”. Tentang yang biasa dilakukan orang dan tidak biasa dilakukan
orang. Tentang mainstream dan anti mainstream. Saya banyak merenung
tentang kenyataan bahwa jalan hidup saya ternyata tidak seperti jalan hidup mayoritas
orang. Dan akhirnya membuat saya bertanya-tanya, apa nanti kata orang? Apa yang
harus saya jelaskan pada mereka?
Akibatnya saya jadi banyak berkubang dengan kebingungan bahwa seharusnya
saya menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya.
Apakah menjadi berbeda itu
salah?
Sejak ada di bangku sekolah, menjadi berbeda itu hanya ada dua
pilihannya. Nerd atau trendsetter. Tapi alih-alih menjadi trendsetter, orang-orang yang ‘kuat
mental’ untuk menjadi berbeda, lebih memilih untuk dikatakan nerd. Selebihnya, (dan saya yakin
termasuk golongan ini) memilih untuk menjadi kekinian seperti anak-anak gaul
yang ada di sekolah. Saya jadi ingat, saat SMA, betapa bencinya saya dengan
gaya bahasa SMS yang “gaul” itu. You know,
yang nulis aku aja jadi aqu atau Q. Ugh! Saya kesel banget sebenernya. Tapi
saat itu saya berfikir, kalau saya engga nulis SMS dengan bahasa begitu, saya
tidak termasuk dalam dunia remaja kekinian, dan itu artinya saya nerd. Untuk status sosial yang lebih
baik, maka ikut-ikutan lah saya menulis SMS dengan gaya begitu. Walau aslinya
saya merasa jijik dengan gaya SMS begitu.
Di bangku sekolah menjadi berbeda itu tidak mudah ternyata. Mungkin
itulah awal mula, bahwa ternyata saya ini, sangat sangat sangat terbiasa dengan
menjadi seragam. Saya takut malah menjadi berbeda.
Makanya, dari dulu saya selalu merasa bahwa
saya ini mainstream. Terbukti dari tidak
ada hal yang berbeda dari apa yang saya lakukan. Saya tidak berpenampilan
nyentrik atau bergaya yang aneh-aneh. Saya bukan vegetarian, saya suka makan
mie, saya juga lebih memilih menggunakan sepeda motor ketimbang sepeda. Dan
saya juga suka musik-musik top 40. Tuh kan, tidak ada hal-hal yang saya
lakukan, yang mengindikasikan kalau saya ini seorang yang anti mainstream.
Hingga sebuah percakapan terjadi.
Teman baik saya menyentil dengan berkata, “Banyak orang, yang anti mainstream-nya tuh cuma
luarnya aja. Tapi dalemnya mah sama… pikirannya mainstream. Kalau kamu itu
luarnya mainstream, pake baju aneh aja engag pede, cuma kalau dibedah, kamu tuh
anti mainstream!”.
Tentu saja saya GEER setengah mati dibilang
begitu. Sambil tersipu saya jawab “Ah
masa sih?” Lalu teman menimpali dengan, “Tapi
masalahnya kamu sendiri yang pengen jadi mainstream.. semua orang pengen jadi
anti mainstream Peh, kamu udah anti mainstream, tapi pengennya mainstream. Tuh
kan, kamu emang anti mainstream”.
Ah apa iya? Apakah saya terobesi menjadi
seragam, di saat saya justru sudah memiliki jalan yang berbeda?
Percakapan dengan teman saya itu akhirnya memberikan saya tamparan,
bahwa ternyata tidak semua orang diberikan kepercayaan diri dan kekuatan untuk
mensyukuri apa yang ada. Dan yang paling menyedihkan, ternyata tidak semua
orang sanggup menjadi berbeda.
Sebelum percakapan itu terjadi, saya adalah contoh orang itu. Saya
yang tidak pede, saya yang merasa harus sama, dan saya yang kurang
bersyukur.
Tapi kini saya sudah lebih siap menerima kenyataan bahwa saya ini anti mainstream dalam tataran yang lebih
spesifik. Bukan soal fashion atau
referensi musik musik tapi tentang pandangan dan pilihan-pilihan hidup.
Pada akhirnya saya harus belajar bahwa
tidak semua orang harus tau dan paham mengenai alasan-alasan pemilihan hal-hal
di hidup saya ini. Toh saya juga tidak punya tanggung jawab apapun kepada
mereka. Dan yang kedua, saya harus belajar lebih keras lagi untuk bisa menerima
garis hidup yang berbeda dari orang lain.
Semua orang harus berani untuk menjadi
berbeda. Jangan takut jadi anti
mainstream! Karena menjadi berbeda itu sah-sah saja.
Mari bersyukur, mari merayakan hidup.
Cheers,
A
#31harimenulis
#Penutup
#Bonus